Sekolah menjadi institusi paling penting saat ini, orang yang tidak masuk kedalamnya diyakini kelak akan hidup sengsara. Tidak mengherankan jika setiap tahun ajaran baru, selalu terjadi perlombaan orangtua untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Semakin favorit, akan semakin terjamin masa depan anak.
Sekolah dianggap sebagai lembaga super, tempat mencetak orang-orang menjadi baik dan pintar. Wajar jika kemudian para orang tua menyerahkan fungsi pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah dan menggantinya dengan membayar iuran rutin.
Begitupun ketika korupsi mewabah di Indonesia. Sekolah dijadikan sebagai benteng terakhir perlawanan. Bahkan sewaktu bertemu dengan koalisi antarumat beragama untuk antikorupsi, Mendiknas Bambang Sudibyo sempat akan memasukkan materi mengenai antikorupsi ke dalam kurikulum.
Sebagai lembaga pengajaran nilai-nilai kebaikan, sekolah diharapkan memiliki peran besar dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi. Walaupun menjadi tempat menyemai harapan, bukan berarti peran dan fungsi sekolah tidak ada yang mengkritik. Malah banyak di antaranya menyatakan sekolah bagian dari masalah di masyarakat. Seperti Ivan Illich yang menginginkan masyarakat dibebaskan dari belenggu sekolah (Yayasan Obor Indonesia, 2000) atau Roem Topatimasang yang menganggap sekolah sebagai candu (Insist, 2001).
Sekolah divonis gagal menjalankan fungsinya. Sebagai institusi pengajaran, tempat melatih keterampilan peserta didik mengantisipasi dan menciptakan teknologi, ternyata sekolah tidak mampu berbuat apa-apa dan jauh tertinggal oleh tempat-tempat kursus. Sementara sebagai institusi pendidikan, yang mengantarkan siswa menjadi manusia paripurna, sekolah ternyata juga mandul, malah menjadi penjara yang membunuh kreativitas dan potensi siswa serta menghambat proses pemanusiaan.
Lantas bagaimana dengan kemampuannya menjadi tempat memulai perjuangan melawan korupsi di Indonesia yang telah memasuki stadium tiga seperti sekarang? Jawabannya adalah pertanyaan; apakah produk sekolah, SD hingga SMA, yang setiap tahun meningkat menambah koruptor atau menambah orang yang taat hukum? Tentunya sangat sulit untuk mengukur bahkan barangkali alat-alat ukurnya pun tidak ada.
Jalan termudah adalah melihat bagaimana cara sekolah bekerja, terutama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran terhadap siswa. Apabila merujuk taksonomi pendidikan-nya Benjamin S Bloom, ada tiga ranah kemampuan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).
Sebelum mengajar, guru biasanya membuat satuan pelajaran (satpel), termasuk di dalamnya menentukan tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK). Satpel umumnya dipaksa mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apalagi dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai 2004.
Memang, jika ingin menjadi lembaga yang bisa mendorong usaha pemberantasan korupsi, titik tekan tentunya ada pada kemampuan afektif dan psikomotorik. Murid didorong tidak hanya mengetahui apa itu korupsi, seperti apa dampaknya, dan bagaimana cara memberantasnya. Tapi yang lebih penting bagaimana murid menerapkan nilai-nilai antikorupsi seperti menghormati hak orang lain atau taat pada hukum.
Namun, praktiknya, kegiatan belajar-mengajar di sekolah lebih menekankan pada kemampuan kognitif. Murid masih menjadi celengan guru, menghafal semua pelajaran yang kemudian keluar saat ujian. Secara kognitif murid diajarkan supaya jujur, taat hukum, tenggang rasa, dan peduli pada sesama, tetapi sebatas teori. Akibatnya, kemampuan maksimal murid hanya sebatas hafal pada nilai-nilai kebaikan. Tidak mengherankan jika ada murid yang jago tawuran tapi nilai pendidikan moralnya sangat bagus.
Justru yang sering kali dilupakan adalah pelajaran informal, terutama menyangkut perilaku guru maupun kepala sekolah. Bagaimana sikap mereka dalam mengelola sekolah, merupakan pelajaran yang dengan efektif bisa membentuk sisi afektif (sikap) siswa. Sayangnya, pelajaran tersebut justru sering kali berbeda dengan yang diajarkan di ruang kelas (kognitif).
Sejak pendaftaran hingga lulus, murid dipertontonkan bagaimana praktik korupsi. Ketika mendaftar, mereka dibebani segala macam biaya; bangunan, buku pelajaran, kebersihan, atau seragam. Bahkan mereka yang kemampuan akademis di bawah standar, kadangkala bisa membeli kursi. Pelajaran awal yang didapat murid dari sekolahnya adalah cara menyuap.
Sewaktu belajar di sekolah, murid diajarkan tidak mengambil hak orang dengan alasan apa pun, tapi pada saat bersamaan, tanpa ada aturan yang jelas, dia harus membayar hampir semua aktivitasnya. Walau sudah membayar iuran bulanan, setiap kali ujian diminta mengganti biaya fotokopi soal, jika tidak lulus, asal mau bayar masih bisa mengikuti ujian susulan. Begitupun sewaktu olahraga, masih dikutip iuran renang atau lapangan, jika malas ikut, asalkan bayar akan tetap diberi nilai.
Selain itu, perilaku kepala sekolah terutama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) turut memberi pengaruh pada murid. Murid secara tidak langsung diajarkan agar tertutup dalam mengelola dana publik; merahasiakan jumlahnya, dari mana sumbernya, dan akan digunakan untuk apa saja. Termasuk tidak memberi pertanggungjawaban pemakaiannya secara reguler.
Begitupun ketika akan lulus. Sekolah menyodorkan berbagai biaya seperti ujian akhir, perpisahan, atau menebus ijazah. Murid diancam tidak boleh ikut ujian atau mendapat ijazah jika tidak bisa menyelesaikan urusan tersebut. Pelajaran terakhir dari sekolah adalah cara memeras.
Apabila ada yang ditanya apa yang paling diingat ketika sekolah, tentu jawabannya bukan pelajaran tapi perilaku guru atau kepala sekolah. Korupsi yang dipraktikkan guru atau kepala sekolah merupakan pelajaran yang akan terus diingat. Akhirnya sekolah bukan menjadi benteng antikorupsi, tapi tempat terbaik untuk belajar korupsi.
Akan tetapi, sangat tidak adil jika guru atau kepala sekolah yang disalahkan. Karena mereka hanya mencontoh sekaligus korban birokrasi di atasnya, seperti pejabat di dinas pendidikan atau Depdiknas. Untuk menjadi guru atau kepala sekolah harus ada uang setoran, agar sekolah mendapat bantuan program atau proyek mesti disediakan fee dan uang jasa, ketika pengawas datang harus dibekali uang transportasi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ah!
(Repost dari Ade Irawan, Pernah Menjadi Guru, Kini Aktif di Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan untuk rekan - rekan guru - Tulisan ini disalin dari Kompas, 28 September 2005)
Senin, 03 Maret 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



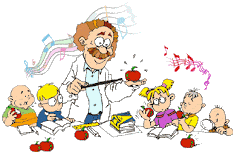
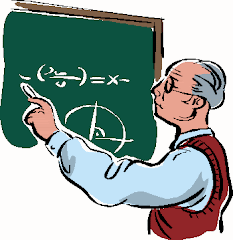








Tidak ada komentar:
Posting Komentar